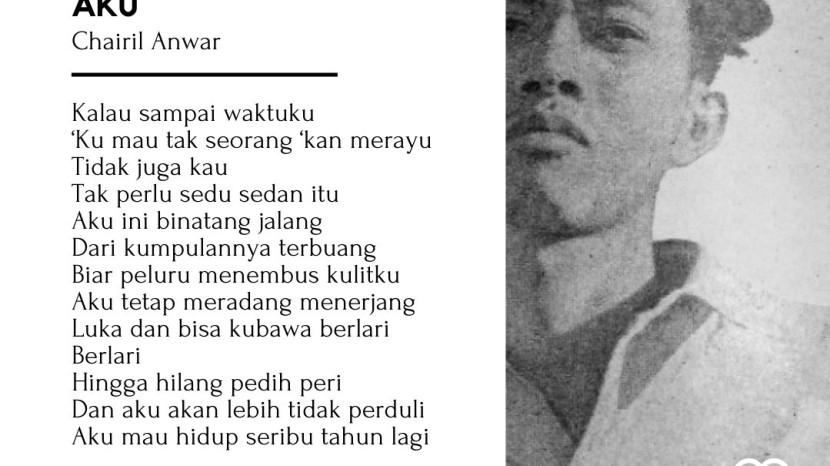Resensi Buku
Resensi Buku Anjing yang Mencintai Bunga, Antologi Puisi yang Kaya Rasa dari Lima Penyair
Kesan pucat langsung tertangkap ketika menghadapi buku Anjing yang Mencintai Bunga: Antologi Puisi Lima Penyair.
TRIBUNJATENG.COM - Kesan pucat langsung tertangkap ketika menghadapi buku Anjing yang Mencintai Bunga: Antologi Puisi Lima Penyair.
Mungkin kesan itu hadir karena font judul yang meski berwarna merah tapi terlalu ramping, agak kalah oleh latar belakang lukisan yang cenderung bernuansa abu gelap.
Apakah puisi-puisi dalam antologi ini sepucat sampul bukunya?
Antologi Anjing yang Mencintai Bunga, yang diluncurkan di Kendal, pada 5 November 2021 silam, berisi puisi-puisi lima penyair, yakni Achiar M Permana, Beno Siang Pamungkas, Slamet Priyatin, Soekamto, dan Timur Sinar Suprabana. Buku puisi ini dibuka oleh 17 puisi Achiar M Permana dan seturut abjad ditutup oleh 15 puisi Timur Sinar Suprabana.
Baca juga: Cara Warga Nonton Balapan Gratis di Sirkuit Mandalika: Pergi ke Bukit, Panjat Pohon Hingga Naik Truk
Baca juga: Syahrini Pilih Temani Reino Barack Bisnis, Sekali Jalan Dapat Komisi 3 Kali Lipat Manggung
Saya sangat mengamini judul kata pengantar Gunawan Budi Susanto yang menyatakan bahwa “Mereka Penyair, Sebenar-benar penyair”.
Proses kelima penyair Anjing yang Mencintai Bunga dalam dunia kepenyairan yang tidak instan menjadikan syair-syair yang mereka tulis mempunyai roh sehingga kata-kata yang tertulis tidak hanya menjadi kata yang sekadar terbaca, namun mampu membawa pembaca merasakan apa yang dirasakan dan disaksikan pencipta syairnya.
Puisi- puisi Achiar M Permana --seperti biasa-- kaya dengan diksi, yang jika pembaca tak mempunyai kosakata cukup, harus meluangkan waktu untuk mencari padanan kata tersebut dalam kamus, baik kamus berbahasa Indonesia maupun kamus berbahasa Jawa.
Penyair yang memenangi Penghargaan Prasidatama 2020 untuk kategori antologi puisi terbaik dari Balai Bahasa Jawa Tengah ini sering menghadirkan kata-kata berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia, yang kadang terasa asing bagi pembaca.
Tak jarang pula terselip kutipan dialog berbahasa daerah dan asing, dalam puisi karya penyair yang pernah membuka Kelas Menulis Puisi di Kedai Kopi Kang Putu, Gebyog, Gunungpati, Kota Semarang ini.
Dalam puisi tentang Bung Hatta, misalnya, Achiar menukil pertanyaan Bung Karno saat Bung Hatta menjenguknya, ‘Hoe Gaat Het Met Jou”, sebagai judul puisi.
Puisi “Hoe Gaat Het Met Jou” ini sebetulnya tak berisi peristiwa Bung Hatta menjenguk Bung Karno, tapi lebih kepada kegelisahan penyair yang mengadu kepada Bung Hatta tentang karut-marut zaman saat puisi itu ditulis. Kegelisahan penyair tentang ganasnya pandemi Covid-19 yang membuat rakyat pontang-panting menyelamatkan nasibnya tertuang pada bait yang berbunyi; “//sejak pagebluk menunjang/serupa babi hutan luka tembiang/ganas merampang/kami jatuh terjengkang/rubuh membungkang/:kehilangan pegang//”, ditulis dengan cantik menggunakan kata yang “memaksa” pembaca harus membuka kamus untuk lebih bisa mengerti isi puisi.
Begitu pula dengan 16 puisi Achiar lainnya.
Pembaca yang tidak malas akan belajar banyak kosakata baru lewat puisi-puisi penulis kumpulan puisi Sepasang Amandava (2019) ini, sekaligus dibawa menjelajahi rasa sang penyair dalam memandang sebuah peristiwa.
Berbeda dari 20 puisi Beno Siang Pamungkas, yang lebih banyak menggunakan kata gampang dimengerti dan tidak terlalu mengejar rima.
Tapi, bukan berarti puisi-puisi Beno kalah indah.
Jika saya serasa nggetem saat membaca puisi Achiar, saya menemukan kekaleman yang menghanyutkan pada puisi-puisi Beno Siang Pamungkas.
Di balik kata sederhana yang tertulis, saya menemukan pesan tersirat yang tidak sederhana seperti yang terdapat pada puisi berjudul “Bulan”, kepedihan yang mendalam pada puisi “Kayu Bakar”, dan haru seorang anak pada ibunya pada puisi berjudul “Ibu”.
Kegeraman penyair pada carut marut kondisi negara juga tersaji secara apik, lembut namun tidak kehilangan ketajamannya.
Dalam buku antologi ini, pembaca tak melulu menemukan syair-syair yang membabar kahanan.
Bagi penggemar puisi cinta, pembaca akan dimanjakan oleh 15 puisi cinta besutan Slamet Priyatin yang sudah pasti membuat rasa para pembaca terojeng-rojeng.
Dalam puisi-puisi tentang Bukares, ibu kota Rumania, sang penyair seperti membawa pembaca pada perasaan nglangut, yang bahkan tak terobati oleh keindahan Bukares, yang terwakili oleh gedung kuno, tembang klasik, balet, dan lukisan, dan bahkan rindu yang sangat bagi sang penyair bisa lebih memabukkan daripada anggur.
Syair-syair Slamet Priyatin membuat saya bisa melupakan sejenak keruwetan kasunyatan hidup, yang disajikan dua penyair sebelumnya.
Mungkin betul kalau cinta sekali pun itu berupa kegalauan, bisa sedikit mengobati kepahitan.
Saya harus belajar banyak dari Slamet Priyatin untuk hal yang satu ini.
Puisi-puisi selanjutnya milik penyair kelahiran Semarang, 3 November 1965, yang aktif menulis sejak SMP, Soekamto Gullit.
Sebanyak 18 puisi yang lahir pada kisaran 2009 hingga 2018 ini tak diragukan lagi kekuatan keindahannya.
Sayang, kenikmatan saya saat membaca syair-syair Soekamto sedikit terganggu dengan penggunaan kata depan “di” yang seharusnya diletakkan terpisah malah dirangkai, seperti, disepanjang, digerbang, dikejauhan, diperkebunan, dalam puisi berjudul “Wanita Paro Baya” dan beberapa puisi lain.
Saya sempat berpikir, peletakan “di” yang tidak tepat ini memang disengaja.
Namun, saat membaca Sajak di Balik Pertemuan, saya menemukan ketidakkonsistenan penerapan “di” yang sama-sama menyatakan tempat ditulis, tapi dengan cara berbeda.
Kehadiran seorang editor mungkin sangat diperlukan, sekalipun buku yang akan diterbitkan berisi tulisan-tulisan seseorang yang sudah tidak lagi diragukan kepiawaiannya di dunia sastra.
Untuk menghindari kesalahan-kesalahan serupa.
Penyair besar Timur Sinar Suprabana menjadi gong penutup buku antologi puisi dengan 15 puisi yang manis.
Ibarat sebuah perjamuan, buku ini adalah perjamuan yang sempurna.
Diksi-diksinya melentik indah seperti penari.
Kata-kata yang bagi pembaca menjadi kata biasa seperti, mbuh, selfie, bahkan nama Jokowi bisa terangkum indah menjadi puisi getir tentang ironi “Kota Lama” yang hanya menjual imitasi masa lalu.
Membaca buku dan menyaksikan acara peluncuran buku antologi puisi lima penyair berjudul Anjing yang Mencintai Bunga pada akhirnya menyadarkan penikmat puisi seperti saya, bahwa menulis puisi adalah proses tiada akhir.
Kata dalam puisi adalah seperti proses beras menjadi sake.
Butuh waktu lama dan mengendap untuk dapat dinikmati dan menjadikan penikmatnya kepayang, bukan hanya proses menjejerkan sebanyak mungkin kata dan lalu meletreknya dalam waktu lima menit seperti proses meletrek nasi menjadi sega aking di nampan, seperti yang diajarkan seorang profesor yang sempat menghebohkan media sosial dengan kursus membuat puisi selama lima menit berbayar lima puluh ribu rupiah.
Baca juga: Hendri, Napi Lapas Kedungpane yang Jadi Penadah Sabu Dipindahkan ke Blok Maximum Security
Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Big Match Persis Solo Vs PSIM Yogyakarta Liga 2 2021
Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan sega aking.
Ia tetap bisa digoreng dan dinikmati sebagai cemilan kala gabut, meminjam istilah anak sekarang untuk menyatakan kebosanan.
Tapi sega aking tak akan pernah bisa disebut sake, ia tak akan pernah bisa membuat kepayang meski sama-sama berbahan dasar beras.
(Mugi Astuti, mantan TKW, ibu rumah tangga, peserta kelas menulis Kedai Kopi Kang Putu)
Judul buku: Anjing yang Mencintai Bunga
Penulis : Achiar M Permana dkk
Penerbit : Cipta Prima Nusantara, Semarang
Cetakan : I, November 2021
Tebal : 134 + xvi halaman
ISBN : 978-623-380-056-3