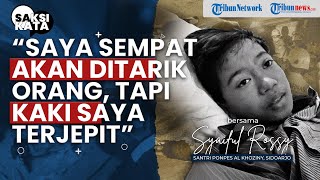OPINI
OPINI : Membangun Kecerdasan Ekologis Memanfaatkan Air Hujan
MUSIM hujan hampir identik dengan adanya bencana. Apalagi adanya pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan tingkat curah hujan menjadi tinggi
Oleh Udi Utomo, SS, MPd
Guru SMP N 5 Pati
MUSIM hujan hampir identik dengan adanya bencana. Apalagi adanya pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan tingkat curah hujan menjadi tinggi.
Tingkat curah hujan tinggi menimbulkan banyak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang sekarang banyak melanda beberapa wilayah di Indonesia.
Padahal ada banyak yang bisa dimanfaatkan dari air hujan jika dikelola dengan baik. Sayangnya melimpahnya air hujan tersebut tidak dimanfaatkan dan hanya dibiarkan terbuang percuma.
Tidak adanya pengelolaan air hujan dengan baik tercermin dari masih rendahnya kepemilikan jenis resapan air oleh rumah tangga.
Dari tiga jenis resapan yang paling banyak adalah taman atau tanah berumput dibandingkan sumur resapan dan lubang biopori.
Datanya menyebutkan jenis resapan air dengan taman atau tanah berumput 24 persen, sedang sumur resapan 4,9 persen dan lubang biopori 2,1 persen (BPS, 2017).
Tidak dimanfaatkannya air hujan juga tercermin dari penggunaan air hujan untuk sumber air rumah tangga.
Datanya menunjukkan 65,56 persen rumah tangga menyatakan tidak pernah menggunakan air hujan dan yang selalu menggunakan air hujan untuk sumber air rumah tangga hanya 3,7 persen (BPS, 2017).
Pemanfaatan air hujan untuk air minum juga tergolong kecil yaitu hanya 2,18 persen, yang paling tinggi menggunakan air minum dalam kemasan (AMDK) yaitu 39,34 persen (BPS, 2020).
Akibat disia-siakannya air hujan, lembaga World Resources Institute memprediksi dunia akan menghadapi ancaman krisis air bersih, selain karena perubahan iklim dan pertambahan jumlah penduduk.
Sedang ketersediaan air bersih per kapita Indonesia terus menurun. Pada 2010 ketersediaannya 265.450 mm kubik per kapita per tahun, 2015 menjadi 240.584, 2020 menjadi 220.428, dan diprediksi pada 2035 menjadi 181.498 (Kompas, 3/12/2021).
Dari data-data tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan air hujan masih kurang.
Padahal Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 2.000 sampai 3.000 mm per tahun.
Perlu adanya gerakan budaya menyimpan dan mengelola air hujan agar tidak terbuang sia-sia.
Perlu tindakan yang optimal dalam pemanfaatan dan pengelolaan air hujan sehingga memberikan manfaat.
Ekopedagogik
Perilaku menghemat air dan memanfaatkan air hujan dapat diajarkan sejak dini. Internalisasi nilai-nilai ini dapat melalui pendidikan.
Ekopedagogik bisa menjadi alternatif. Merujuk The First Earth Summit di Rio de Jeneiro 1992, para akademisi mendefinsikan ekopedagogik sebagai pedagogi yang mengusung konsep belajar untuk memaknai makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari manusia.
Menurut Khan (dalam Supriatna, 2016) mendifinisikan ekopedagogik sebagai gerakan akademik untuk menyadarkan siswa menjadi individu yang memiliki pemahaman, kesadaran dan keterampilan hidup yang selaras dengan dengan kepentingan pelestaraian alam.
Sebagai bagian dari pedagogik kritis, ekopedagogik mengembangkan pembelajaran transformatif (kurikulum praksis sebagai pembelajaran).
Guru mengembangkan kurikulum tertulisnya dengan materi pembelajaran yang merupakan konstruksi persoalan-persoalan lingkungan di sekitar siswa.
Pembelajaran merupakan refleksi antara guru dan siswa terkait persoalan-persoalan nyata di kehidupan sekitar siswa (kontekstual).
Penilaian atau output dari pendekatan ekopedagogik adalah karakter yang ditunjukkan siswa pada penguasaan pengetahuan, kesadaran dan aplikasi hidup ramah dengan lingkungan (kecerdasan ekologis).
adi kinerja siswa harus nampak dalam praktik kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sekedar menghafal dan mengingat konsep.
Kecerdasan ekologis memadukan antara keterampilan kognitif (pengetahuan) dengan empati terhadap segala bentuk kehidupan.
Siswa yang memiliki kecerdasan ekologis akan menunjukkan empatinya seperti merasa sedih saat melihat tanda-tanda “penderitaan” bumi, dan bertekad melakukan tindakan untuk membantu melestarikan bumi.
Siswa diajak berpikir kritis bahwa setiap tindakannya dalam memenuhi kebutuhan hidup selalu berdampak pada lingkungan.
Media atau materi internalisasi nilai-nilai kecerdasan ekologis dapat menggunakan ajaran-ajaran kearifan lokal masyarakat setempat.
Kearifan lokal yang telah dipraktikan oleh masyarakat adat atau masyarakat tradisi yang berhubungan dengan konsep sustainability (kesinambungan).
Sedulur Sikep
Misalnya praktik kearifan lokal masyarakat Samin (sedulur sikep). Pada sedulur sikep mengajarkan penyandaran pada sawah (bumi) sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan (mewarisi) kognisi ajarannya pada anak-anak mereka.
Mereka memaknai tanah sebagai “Ibu”.
Pada masyarakat Samin menganut pola sikep rabi yaitu masyarakat yang bertumpu pada alam dan alam pertumpu pada manusia.
Mereka mengutamakan harmonisasi hidup dengan alam yaitu dengan mengambil atau memanfaatkan sesuai kebutuhannya saja. Sikap ini sebagai wujud pelaksanaan dari lima prinsip dasar ajaran sedulur sikep (adeg-adeg) yaitu
(1) ojo drengki srei, tidak boleh memiliki rasa dengki, iri,
(2) ojo dakwen panasten, yaitu tidak boleh memiliki rasa curiga terhadap sesama,
(3) ojo bedhog colong, tidak boleh mencuri,
(4) ojo methil jumput, mengambil sesuatu yang bukan haknya,
(5) ojo nemu, tidak boleh mengambil barang orang lain yang terjatuh karena bukan miliknya (Sugihardjo, 2013).
Selanjutnya untuk menumbuhkan kecerdasan ekologis, siswa dapat diajak untuk mengunjungi lokasi masyarakat tradisi terdekat dari sekolah sehingga siswa melihat langsung bagaimana masyarakat tradisi dalam menjaga sumber airnya.
Kearifan lokal
Selain internalisasi nilai kearifan lokal, praktik penumbuhan kecerdasan ekologis dapat melalui praktik di sekolah.
Misal untuk mengurangi konsumsi air kemasan. Siswa diminta membawa botol minuman refil (isi ulang) dari rumah dan mengajurkan untuk mengurangi konsumsi minuman berpengawet dan berpemanis buatan dengan air putih.
Praktik lainnya praktik menghemat air di toilet dengan melatih siswa menggunakan air di toilet dengan bijak seperti mematikan keran saat tidak dipakai dan mempraktikan cara menyiram kotoran dengan menggunakan air secukupnya.
Praktik memanfaatkan air daur ulang untuk tanaman di sekolah yaitu dengan melatih para siswa menyiram dan memelihara tanaman dengan menggunakan air daur ulang.
Penumbuhan kecerdasan ekologis harus didukung pula oleh budaya sekolah.
Budaya sekolah yaitu sekumpulan norma, nilai, dan tradisi yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga sekolah dan mengarah ke seluruh aktivitas personel sekolah (Daryanto, 2015).
Budaya sekolah yang dapat dikembangkan untuk menumbukan kecerdasan ekologis antara lain dengan membiarkan halaman sekolah tetap terbuka untuk resapan air hujan, menyediakan lebih banyak sumur resapan di seluruh kawasan sekolah agar air hujan bisa segera masuk ke dalam tanah.
Menampung air hujan dan mengolahnya menjadi air minum bagi kepentingan komunitas di sekolah, mengembangkan gerakan hanya mengkonsumsi air olahan di sekolah tanpa tergantung pada produksi air kemasan.
Dan menerapkan kebijakan green school yaitu sekolah yang menjungjung tinggi konsep sustainability dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. (*)
Baca juga: Hotline Semarang : Halo BPN Kenapa Berkas Pengukuran Tanah Lama Jadinya?
Baca juga: 10 Mantan dan 5 Anggota DPRD Muara Enim Jadi Tersangka Kasus Suap
Baca juga: Fokus : Wisatawan Bencana
Baca juga: Penjelasan Pelatih Persib Bandung soal Cedera Marc Klok