Readers Note
UUD 1945 Di Era Neo-Liberalisme
Dalam ketatanegaraan, fase pergeseran model Liberalisme tersebut menandai pergeseran gagasan Negara Penjaga Malam menuju Negara Kesejahteraan
UUD 1945 Di Era Neo-Liberalisme
FX.Adji Samekto
Guru Besar Universitas Diponegoro | Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022
NEOLIBERALISME dapat didefinisikan sebagai bentuk baru Kapitalisme. Neoliberalisme yang mewujud dalam pengurangan peran negara, muncul kembali pada era pemerintah Presiden AS, Ronald Reagan (1981-1989) dan Perdana Menteri Inggris Margareth Tatcher (1979-1990) yang kemudian diteruskan oleh pemerintahan Presiden AS Bill Clinton (1993-2001) serta Perdana Menteri Inggris Tonny Blair (1997-2007).
Neoliberalisme yang muncul kembali pasca globalisasi tahun 1990 itu sangat mendorong negara-negara untuk melakukan privatisasi, debirokratisasi serta deregulasi, untuk mendukung ekonomi pasar. Berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia WTO semakin memperkuat pembenaran keberlakuan ekonomi pasar.
Secara historis, paham Liberalisme lahir di Eropa sesudah Revolusi Perancis 1789. Liberalisme model klasik ini menuntut minimalisasi peran negara. Hingga akhirnya pada awal abad 20, Liberalisme model awal itu harus diubah menjadi Liberalisme yang memberi ruang bagi negara untuk berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Dalam ketatanegaraan, fase pergeseran model Liberalisme tersebut menandai pergeseran gagasan Negara Penjaga Malam menuju Negara Kesejahteraan (Welfare State). Ketika merancang lahirnya negara Indonesia, para pendiri bangsa ini juga menerima gagasan Negara Kesejahteraan tetapi ditransformasikan dalam konteks keindonesiaan dan penjabarannya dituangkan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.
Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1970-an, praktik negara-negara dalam menjalankan gagasan Negara Kesejahteraan, telah menimbulkan kecenderungan over-regulated, karena negara semakin banyak membuat aturan-aturan dalam bidang-bidang kebijakan kesejahteraan. Praktik Welfare State di era 1970-an ini ternyata membawa negara-negara terjebak dalam hutang-hutang yang justru mempersulit negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya.
Itulah sebabnya, Ronald Reagan dan Margareth Tatcher, pemimpin-pemimpin negara adidaya yang berpengaruh waktu itu, memulai upaya kembali minimalisasi peran negara. Pada fase inilah awal dunia didorong masuk globalisasi. Dalam rangka itu, WTO semakin mendorong negara-negara untuk melakukan deregulasi, debirokratisasi, maupun privatisasi, karena ketiganya memberi manfaat bagi kelancaran investasi suatu negara ke negara lain, tanpa banyak gangguan prosedur yang menghambat investasi.
Sampai hari ini dorongan atas ketiga hal itu, terus dikumandangkan dengan berbagai pembenaran. Bahkan dari penganut ekonomi pro-pasar, ada dorongan-dorongan privatisasi atas sektor-sektor publik yang menguasai hajat hidup rakyat, termasuk sumber daya alam. Hal ini membawa implikasi ekstrim yaitu penolakan terhadap peran-peran negara dalam konteks Negara Kesejahteraan.
Akhirnya budaya pro-market ini secara sadar atau tidak, diterima sebagai suatu kebenaran, sehingga upaya campur tangan negara untuk kepentingan publik atas beberapa hal cenderung dicurigai sebagai upaya dominasi negara. Resolusi PBB, kebijakan Bank Dunia,WTO dan IMF yang merefleksikan kebijakan pro-market dan Liberalisme lalu dikamuflase sebagai keinginan universal.
Pada giliran lebih lanjut, budaya konsensus pro-market, kini terinternalisasi pada sebagian besar generasi muda yang lahir di era tahun 1980-an. Secara kebudayaan, upaya penerimaan kebenaran Neo-Liberalisme dilakukan dengan membangkitkan pandangan-pandangan tentang betapa pentingnya kebebasan individu, keamanan individu, penekanan tentang penghormatan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara atas kehidupan rakyatnya, serta pentingnya privatisasi.
Penerimaan secara kebudayaan ini pada gilirannya berpotensi mendorong kelompok-kelompok muda untuk mengubah prinsip-prinsip hukum yang sebelumnya telah disepakati dalam hukum dasar tertinggi di suatu negara. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan pendiri bangsa, seolah-olah menjadi salah, karena dianggap tidak mampu menjawab tantangan globalisasi, dan karenanya perlu dirombak.
Nilai-nilai yang dianggap bersifat universal ini lalu cenderung dijadikan batu uji untuk mengukur dinamika politik-sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Inilah ancaman terhadap konsolidasi kebangsaan yang dihadapi Indonesia ketika Neo-Liberalisme diterima sebagai kebenaran yang bersifat universal. Jika bangsa Indonesia tidak pernah mampu mengkonsolidasikan kebangsaan, maka negara ini akan menjadi – apa yang disebut Samuel Huntington (1996) – sebagai negara yang terkoyak (torn country) akibat dominasi Neo-Liberalisme.
Negara yang terkoyak adalah negara yang tidak pernah berhasil mengkosolidasikan kebangsaannya, karena masyarakatnya sendiri terdiferensiasi dalam keinginan-keinginan yang berbeda, mempunyai orientasi peradaban kebangsaan yang tidak pernah jelas karena dominasi “peradaban universal” yang bersumber dari Neo-Liberalisme.
Jelas bahwa tidak perlu kita menerima Neo-Liberalisme, tetapi kita juga harus menghentikan kepura-puraan bahwa sistem ekonomi, hukum, dan pengelolaan sumber daya alam kita, lebih tangguh dalam menghadapi perubahan di era Neo-Liberalisme.















![[FULL] Absennya Megawati di Pidato Kenegaraan Prabowo, Pakar: Bisa Jadi Bola Liar, Harusnya Move On](https://img.youtube.com/vi/V2uym4l-l2w/mqdefault.jpg)







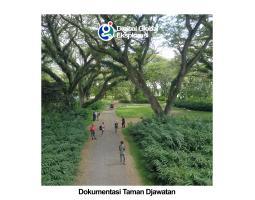




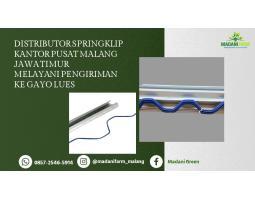













Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.